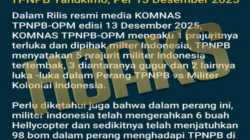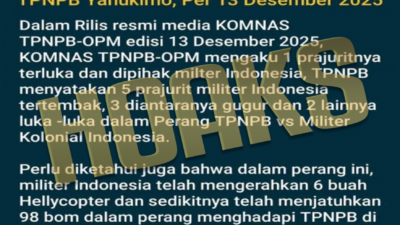Masyarakat di sejumlah wilayah Papua secara terbuka menyatakan keresahan dan kejenuhan mereka terhadap kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kian meresahkan. Banyak warga menyuarakan tuntutan agar negara mengambil langkah tegas terhadap kelompok bersenjata tersebut, yang dinilai tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat Papua, melainkan justru menjadi sumber ketakutan dan penderitaan.
Masyarakat di sejumlah wilayah Papua secara terbuka menyatakan keresahan dan kejenuhan mereka terhadap kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kian meresahkan. Banyak warga menyuarakan tuntutan agar negara mengambil langkah tegas terhadap kelompok bersenjata tersebut, yang dinilai tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat Papua, melainkan justru menjadi sumber ketakutan dan penderitaan.
Tuntutan ini muncul setelah serangkaian aksi kekerasan kembali terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kabupaten Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya. Dalam berbagai insiden tersebut, kelompok bersenjata OPM terlibat dalam penyerangan terhadap aparat keamanan, pembakaran sekolah dan rumah warga, serta pengusiran tenaga pendidik dan kesehatan dari distrik-distrik terpencil.
Tokoh masyarakat dari Lanny Jaya, Markus Tabuni, menyatakan bahwa warga telah lama merasa muak dengan kekerasan yang dilakukan oleh OPM atas nama perjuangan kemerdekaan. “Dulu mereka datang bicara soal kebebasan, tapi sekarang mereka datang hanya membawa senjata dan membuat rakyat takut. Mereka bilang lawan negara, tapi yang diserang rakyat sendiri. Ini bukan perjuangan, ini teror,” tegasnya, Rabu (23/4/2025).
Markus menambahkan bahwa masyarakat lokal, terutama di kampung-kampung terpencil, menjadi korban yang paling terdampak akibat aksi brutal OPM. Warga terpaksa meninggalkan kampung mereka, anak-anak berhenti sekolah, dan akses kesehatan terganggu karena tenaga medis enggan bertugas di zona rawan.
Berbagai tokoh adat, pemuda, dan aktivis perempuan menyuarakan tuntutan yang sama kepada pemerintah agar tidak lagi ragu mengambil langkah tegas terhadap kelompok separatis yang menebar ketakutan. Maria Heluka, aktivis perempuan dari Wamena, menilai negara harus membedakan antara aspirasi politik dan aksi kekerasan.
“Kalau orang bicara damai dan dialog, kita bisa duduk bersama. Tapi kalau orang datang dengan senjata, bakar sekolah, bunuh guru, itu bukan perjuangan. Itu kejahatan. Negara tidak boleh diam,” kata Maria.
Ia juga menyampaikan bahwa banyak perempuan Papua hidup dalam trauma akibat kekerasan yang berkepanjangan. “Kami ingin anak-anak kami sekolah, kami ingin hidup tenang, bukan sembunyi di hutan karena takut ditembak kelompok yang katanya berjuang untuk kami,” tegasnya.
Data dari Yayasan Kemanusiaan Papua Damai mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, sedikitnya 89 insiden kekerasan terjadi di Papua akibat aktivitas kelompok separatis. Dari insiden tersebut, lebih dari separuh korbannya adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.
Direktur yayasan tersebut, Marthen Yaboisembut, menyampaikan keprihatinan terhadap narasi internasional yang kerap menyalahartikan konflik di Papua sebagai konflik antara negara dan rakyat. “Banyak media asing tidak tahu bahwa korban terbesar adalah rakyat Papua sendiri. Mereka pikir OPM mewakili rakyat, padahal rakyat justru takut pada mereka,” jelas Marthen.
Ia menyerukan kepada dunia internasional untuk lebih cermat melihat dinamika konflik di Papua dan mendukung upaya negara dalam menjaga keamanan warga sipil.
Di tengah situasi yang memanas, sejumlah tokoh pemuda dan agama berusaha mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. Forum Pemuda Papua Damai (FPPD) secara aktif menggelar dialog antar kampung untuk menumbuhkan kesadaran damai di kalangan generasi muda.
“Kami ingin menyebarkan pesan bahwa kekerasan bukan jalan keluar. Papua butuh pendidikan, pekerjaan, dan masa depan, bukan peperangan,” kata ketua FPPD, Yunus Kogoya.
Senada dengan itu, tokoh gereja dari Sinode Kingmi Papua, Pdt. Elias Degei, mengingatkan bahwa penderitaan rakyat Papua tidak boleh dijadikan alat politik oleh kelompok manapun. “Rakyat Papua terlalu lama menjadi korban. Saatnya kita bersatu menolak kekerasan dari siapa pun, termasuk dari mereka yang mengatasnamakan perjuangan,” katanya.
Masyarakat Papua kini dengan lantang menyuarakan ketidaknyamanan mereka terhadap keberadaan OPM. Kelompok yang dahulu mengklaim sebagai pelindung rakyat kini dinilai sebagai ancaman nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka bukan lagi simbol perjuangan, melainkan sumber ketakutan dan penderitaan.